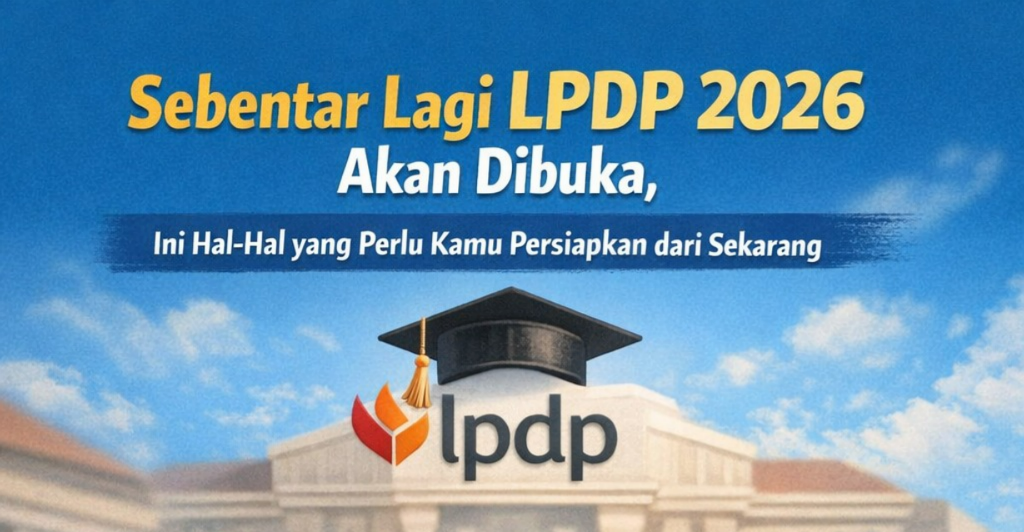- admin@santrimengglobal.com
- Jl. Komplek Bank Niaga Rt. 0015/03 No. 28 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510
Islam, Identitas, dan Solidaritas: Perjalanan Spiritual di Negeri Paman Sam

Amerika, Santri Mengglobal - Jumat, 25 Oktober, kami mengunjungi Kompleks Darussalam di Lombard, pinggiran kota Chicago. Selain masjid sebagai pusat ibadah, kompleks ini memiliki seminary atau pesantren yang mengajarkan studi Islam secara mendalam, mencakup materi akidah, fiqih, hadis, Quran, dan tahfiz untuk berbagai tingkatan usia. Ruang kelas di sini dilengkapi dengan fasilitas modern, mencerminkan kualitas studi di Amerika yang tinggi.
Kompleks ini luasnya mencapai 15 hektar, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti masjid, lebih dari 20 ruang kelas, perpustakaan, fasilitas pemakaman, pusat kebugaran, dapur, dan area parkir yang dapat menampung 400 kendaraan. Sebagai pusat pendidikan, Darussalam tidak hanya berfungsi sebagai masjid tetapi juga sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyediakan kelas-kelas Islam mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan, dipandu oleh ulama muda Amerika yang berkompeten.
Saat tiba, kami disambut oleh seorang Imam yang memperkenalkan fasilitas dan ornamen bangunan dengan rinci. Kami juga dijamu dengan hidangan khas Timur Tengah sebelum melaksanakan salat Jumat. Karena jumlah jamaah yang besar, salat Jumat dilaksanakan dua kali, dan kami mengikuti jadwal pertama. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah keragaman jamaah—banyak di antara mereka adalah Muslim dengan penampilan yang berbeda-beda, mencerminkan latar belakang dari Arab, Turki, Asia Tengah, Afrika, dan negara lainnya. Hal ini terlihat dari wajah serta pakaian khas mereka, seperti jubah Timur Tengah dan penutup kepala dari Asia dan Afrika.
Keberagaman ini menimbulkan pertanyaan dalam benak saya, yang kemudian saya tanyakan kepada Dr. Mahan Mirza, salah satu penanggung jawab program kami dari American Islamic College (AIC). Saya ingin tahu mengapa Muslim di Amerika cenderung menonjolkan identitas keislaman mereka daripada berasimilasi dengan budaya Amerika.
Dr. Mahan menjawab bahwa hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menunjukkan identitas keislaman mereka. Mereka merasa penting untuk mengidentifikasi diri sebagai Muslim di Amerika. Berbeda dengan di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga setiap orang secara otomatis diidentifikasi sebagai Muslim di mana pun berada.
Di sisi lain, saya menilai bahwa keinginan untuk menonjolkan identitas agama di negara lain mencerminkan proses ethnic retention, di mana kelompok minoritas mempertahankan simbol-simbol budaya dan agama sebagai cara untuk menjaga ikatan komunitas dan melawan arus asimilasi yang mengancam identitas kolektif mereka. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor globalisasi, yang memungkinkan mereka tetap terhubung dengan budaya asal dan menjadikan ekspresi keagamaan sebagai bentuk solidaritas transnasional. Maka, identitas Islam di Amerika tidak hanya dihidupi sebagai keimanan pribadi tetapi juga sebagai tanda eksistensi sosial yang dapat memperkuat solidaritas dalam komunitas global Muslim. Hallah, apa sih!
Pada sore harinya, kami juga mengikuti aksi solidaritas mahasiswa Yahudi di Universitas Chicago untuk mendukung perdamaian di Palestina. Acara dimulai dengan makan bersama, diselenggarakan oleh kelompok mahasiswa Yahudi yang menyediakan berbagai makanan, termasuk pho, cokelat panas, dan makanan ramah vegetarian. Setelah makan, Muslim yang hadir mengadakan salat Maghrib berjamaah, diikuti dengan ibadah Shabbat oleh mahasiswa Yahudi, yang terdiri dari pembacaan Mazmur, nyanyian, dan doa. Acara ditutup dengan pidato seorang mahasiswa Yahudi yang menyuarakan kepedulian dan perlawanan mereka terhadap genosida di Palestina. Di tengah suhu malam yang kian dingin, hampir mencapai 8°C, kami melanjutkan acara dengan berkumpul di halaman Universitas untuk berdiskusi dan berbagi pandangan.
Pada satu sisi, kegiatan ini semakin membuktikan apa yang sering saya sampaikan di kelas-kelas saya: bahwa Israel, Zionisme, dan Yahudi adalah tiga unsur yang berbeda. Sikap ketiganya tidak selalu saling memengaruhi, dan menggeneralisasi ketiganya jelas bukan hal yang tepat.
Di sisi lain, kehadiran dan dukungan mahasiswa Yahudi terhadap isu Palestina adalah bukti bahwa konflik dan prasangka masa lalu tidak harus menghalangi niat baik masa kini. Dalam konteks globalisasi yang semakin mempertemukan berbagai budaya dan agama, acara ini mengilhami harapan akan masa depan di mana masyarakat lintas agama dapat bekerja sama dalam misi yang lebih besar: memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan, dan perdamaian global tanpa terbatas oleh latar belakang keagamaan atau identitas.
Setelah semua usai, saya jadi berpikir bahwa makanan memang selalu menjadi hal terpenting di mana pun!
Shafwatul Bary, Peserta program Micro Credential (2024) Chicago, Amerika Serikat, Beasiswa non-Degree Dana Abadi Pesantren Kementrian Agama (Kemenag) berkolaborasi dengan LPDP dan Lembaga Pendidikan di Chicago selama dua bulan.***(Shafwatul Bary)